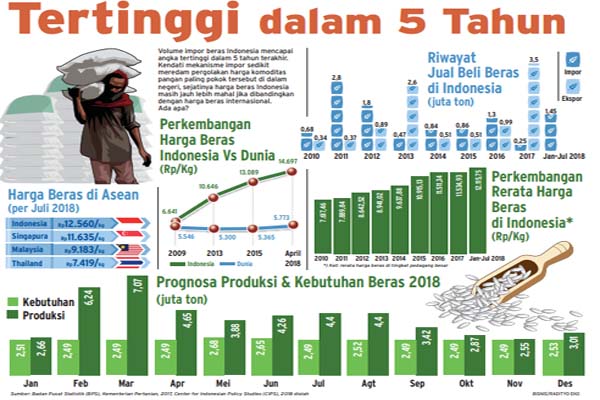Dunia pascapandemi Covid-19 diperkirakan berbeda sama sekali dari saat ini. Itulah normal baru. Dalam Great Depressions (2020), profesor ekonomi New York University, Nouriel Roubini, mengingatkan satu dari 10 potensi depresi ekonomi 2020 ialah deglobalisasi. Antitesis globalisasi ini sebenarnya bukan hal baru. Walden Bello (2003), 17 tahun lalu, mempromosikan ini lewat bukunya yang provokatif, Deglobalization.
Globalisasi, bagi Bello, adalah deretan kegagalan nyata. Itu terlihat dari krisis keuangan berulang, jurang pemisah yang kian lebar antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri, masih adanya ketidaksetaraan besar, dan kemiskinan massal.
Setelah memeriksa malapraktik globalisasi ekonomi yang dipromosikan IMF, WTO dan Bank Dunia, dia mengusulkan pembubaran trio Bretton Wood Institutions ini. Karena bersifat unsustain dan fragile, Bello kemudian menawarkan resep antitesa: deglobalisasi.
Dalam konteks saat ini, deglobalisasi mewujud dalam rupa-rupa proteksionisme, yang sebelum pandemi sudah mulai tampak presedennya, yakni Brexit dan perang dagang antara AS dan China. Disulut pandemi yang merayap secara eksponensial, bagi Roubini, hal itu akan mempercepat deglobalisasi antara China dan AS. Dia menyebut proses itu sebagai 'balkanisasi' dan 'fragmentasi'.
Sebagian besar negara akan merespons dengan mengadopsi kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi perusahaan domestik dan pekerja dari gangguan global. Dunia akan penuh restriksi atas gerak barang dan jasa.
Merujuk Horald James, sejarawan Princeton University, dalam The End of Globalization (2002), akumulasi proses itu berpotensi 'melenyapkan globalisasi'. Proses balkanisasi di tengah pandemi tampak dari pelarangan ekspor hasil pertanian oleh negara produsen dan eksportir pangan. Vietnam, Thailand, dan Myanmar, tiga eksportir penting beras dunia, melarang dan membatasi ekspor.
Dua eksportir gandum dunia, Kazakhtan dan Rusia, menempuh langkah serupa. Kepentingan domestik lebih penting bagi mereka.
Langkah pembatasan ekspor dan tindakan proteksionis lain sebagai respons atas krisis seperti ini juga bukan hal baru. Saat krisis pangan 2007-2008 dan 2011, resep generik itu selalu diulang. Dalam dua periode krisis itu, krisis pangan disulut oleh produksi yang turun dan daya beli warga yang rendah, yang kemudian diikuti ekspektasi penurunan suplai.
Ketika pintu ekspor ditutup, pasar panik dan harga-harga pangan meroket. Plus krisis energi dan spekulasi di pasar komoditas, krisis pangan kian dalam.
Kali ini, menurut FAO (Mei, 2020), produksi pangan, baik biji-bijian (gandum, jagung, kedele, sorgum, beras) maupun buah-sayur, baik. Tak ada laporan gagal panen. Potensi krisis pangan berasal dari guncangan pasokan logistik pangan. Ini menyangkut aktivitas rumit yang menghubungkan produksi di lahan, processing, logistik, pergudangan hingga jasa penjualan di hilir.
Implikasi serius corona tak hanya mengancam produksi di level hulu sebagai konsekuensi kebijakan lockdown tetapi juga mengganggu pengolahan pangan yang padat karya di tengah, dan juga telah memutus (membatasi) lalu-lintas perhubungan dan perdagangan antarbangsa di tingkat hilir.
Negara-negara importir pangan bakal menerima pukulan ganda. Pertama, tidak ada jaminan aliran pasokan karena rantai pasok pangan yang terganggu. Pangan tersedia, bahkan lebih dari cukup tetapi tidak bisa dialirkan ke negara-negara importir yang memerlukan, karena hambatan transportasi dan karantina.
Kedua, harga pangan menjadi mahal seiring terdepresiasinya mata uang negara-negara importir terhadap dolar AS.
Sebagai negara impor pangan yang cukup besar (pada 2018 sebesar US$16,8 miliar), nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara-negara jazirah Arab.
Di luar itu, ada tiga ciri utama geopolitik pangan dunia. Pertama, industri pangan perusahaan transnasional (TNCs) hanya fokus pada sedikit spesies. Misalnya, TNCs hanya fokus pada selusin ternak, 16 (antara lain beras, jagung, dan gandum) dari 3.000 species tanaman pangan yang dibudidayakan, separuh dari 80.000 varietas komersial adalah tanaman hias, pada komoditas aneka kacang hanya fokus pada kedelai dan kacang tanah (ETC Group, 2009; Widianarko et. all., 2003).
Akibatnya, terjadi reduksi luar biasa keanekaragaman hayati, petani semakin tergantung pada paket teknologi (benih, pestisida, pupuk dan lain-lain) dari luar, dan sistem pertanian (negara-negara berkembang) amat rentan.
Kedua, TNCs telah membentuk rantai pangan (agrifood chain). Rantai ini menghubungkan dari sejak gen, bibit, input agrokimia, produksi pangan dan serat, trading dan pengolahan bahan mentah, prosesing dan manufaktur hingga rak-rak di supermarket. TNCs bisa ‘mengawal’ harga input pertanian, mempraktikan perjanjian jual-beli tidak fair, membentuk kartel, mendepak perusahaan lokal dari pasar, dan membeli komoditas petani dengan harga super murah.
Untung besar diraih dengan memeras petani lewat dua cara: mematok harga input dan olahan dengan harga tinggi dan menekan harga beli komoditas petani serendah mungkin. Akibatnya, meski permintaan naik, harga-harga komoditas primer di pasar dunia terus merosot (Eagleton D., 2005).
Ketiga, konsentrasi pangan global di segelintir pelaku. Pada 2011 tingkat konsentrasi pasar dunia oleh empat perusahaan (CR-4), yaitu daging sapi 82%, daging babi 63%, broiler 53%, kalkun 58%, gandum 53%, kedelai 85%, dan jagung 87%. Kecuali gandum, CR-4 ini naik dari kondisi 1999 (Hendrickson M, 2014). Pasar pangan jauh dari pasar sempurna, bahkan mendekati monopoli. Konsekuensinya serius. Harga pangan di pasar dunia tidak stabil.
Konsekuensi arsitektur pangan menjadi, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan 2007-2008 dan 2011 menjadi bukti: harga bergerak bak roller coaster. Kedua, krisis pangan berulang. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik.
Krisis pangan 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, Kamerun, dan Haiti. Krisis pangan 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab. Rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Khadafy di Libya jatuh, karena negara-negara ini 90% pangannya tergantung dari impor.
Pertarungan dalam memenuhi dan mengawal ketersediaan pangan menjadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik.
Bagi Indonesia, seperti amanat UU Pangan No. 18/2012, kita wajib berdaulat di bidang pangan. Pandemi Covid-19 memberi terang baru: amat riskan menggantungkan pangan pada impor. Saatnya merajut daulat pangan.