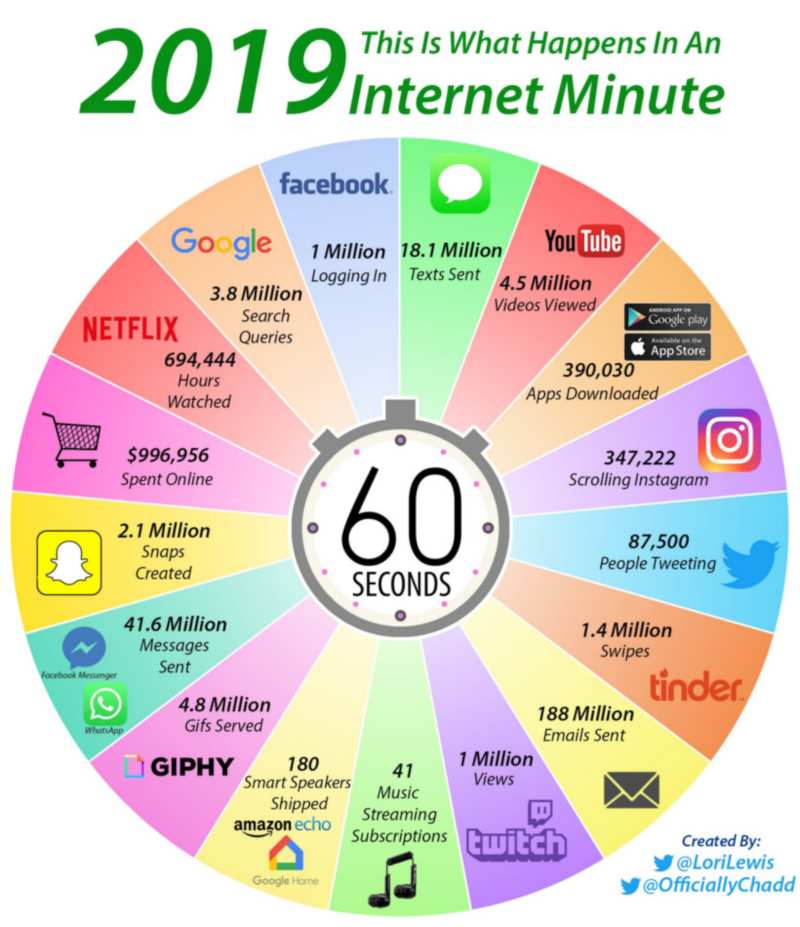Entah ditujukan kepada siapa, seorang eksekutif senior tiba-tiba ‘komplen’, saat membaca satu berita di media online mengenai Garuda Indonesia Rabu (24/4), silam.
Bukan beritanya yang dikomplen, melainkan reaksi pembaca terhadap berita tersebut. “Yang menarik dari semua pembaca 100% merespons, setelah membaca berita itu mereka ‘Sedih’. Masa tidak satu orang pun yang punya pendapat ‘Gembira’, atau ‘Terhibur’ atau ‘Marah’,” begitu komentar bernada komplen dalam sebuah percakapan grup aplikasi pesan.
Tatkala ada yang merespons, bahwa reaksi yang diberikan pembaca bukan ‘Sedih’, melainkan ‘Bangga’, eksekutif ini mengklarifikasi. “Ya, ya ‘Bangga’. Poin saya apa mungkin semua pembaca tiba-tiba ‘Bangga’,” jelasnya memberikan penegasan.
Saya mencoba menjelaskan, mengapa rekasi pembaca itu tercatat 100%? “Sangat bisa jadi, yang memberikan reaksi terhadap berita tersebut baru satu orang.”
Atau, bisa jadi ada 2 orang yang memberikan reaksi yang sama. Kalau dua orang memberi reaksi yang berbeda, tentu angkanya jadi masing-masing 50%. Logika matematika sederhana saja, sebenarnya.
Namun, sang eksekutif masih melanjutkan ‘komplen’-nya lagi. “Saya perhatikan dari beberapa waktu terakhir. Sering komentar pembaca 100 % ‘Gembira’, atau ‘Sedih’, atau ‘Bangga’ atau ‘Marah’ sampai berminggu-minggu,” komentarnya lagi.
Saya tidak ingin menambahkan kelanjutan percakapan tersebut, kendati kemudian muncul bumbu-bumbu lain, bahwa angka 100% itu adalah “kerja mesin”. Kalau itu adalah kerja operator, “tentu reaksinya sedih, marah, sesuai perasaan pemilik” media tersebut. Begitu kira-kira percakapan itu berkembang.
Kira-kira konteksnya begini. Ada berita Rabu lalu, bahwa dua komisaris Garuda menolak untuk menyetujui laporan keuangan perusahaan penerbangan flagship tersebut. Sang Komisaris kebetulan merepresentasi kepemilikan saham dari pengusaha yang kebetulan adalah pemilik media yang membuat berita itu.
Alur spekulasi pun kemudian terbangun, bahwa reaksi pembaca – kolom dengan ikon Senang, Sedih, Marah dst yang biasanya ditaruh di bawah berita – akan dibuat mewakili “kepentingan” komisaris yang mewakili pemilik media yang memberitakan itu.
Tentu, dugaan semacam itu sangat spekulatif. Apalagi kalau lantas muncul semacam “kesimpulan” bahwa mesinlah yang bekerja untuk membuat 100% pembaca memberikan reaksi yang sama.
Padahal, tidak semua pembaca berita selalu memberikan reaksi; entah Senang, Sedih, Gembira, Bangga, atau Terinspirasi terhadap sebuah tersebut. Kalau reaksi itu cuma berasal dari 1 pembaca, jelas ikon yang muncul menjadi 100%. Kalau empat pembaca memberikan reaksi berbeda-beda, masing-masing akan memperoleh porsi 25%. Kalau tiga pembaca yang memberikan reaksi berbeda-beda, masing-masing ikon akan memperoleh 33%. Begitu kira-kira.
Dan reaksi tersebut bukanlah kerja mesin. Tapi kerja manusia, yang membaca berita itu. Kalau reaksi itu tetap 100% selama berminggu-minggu, ya boleh jadi berita tersebut tidak ada yang memberikan reaksi selanjutnya, meski sebenarnya masih terus dibaca. Begitu saja cara mudah memahaminya.
***
Saya sengaja mengangkat contoh percakapan ini sebagai ilustrasi, bahwa informasi digital yang berkembang pesat akhir-akhir ini tidak serta merta memberikan pemahaman secepat kemajuan teknologinya.
Mengapa hal yang tampak sederhana atau sepele itu saya anggap begitu penting? Ya, karena perilaku individual ini bisa mencerminkan perilaku komunal di sebagian masyarakat Indonesia.
Kalau komentar tersebut boleh dijadikan sampel, barangkali pula mewakili banyak isu dan informasi lainnya, yang membentuk opini masyarakat secara cepat, dan meluas. Terfabrikasi. Terlebih apabila ada motif dan kesengajaan untuk membangun opini publik, demi tujuan tertentu.
Saya kok percaya, gambaran itulah yang tampaknya bisa sedikit menjelaskan, mengapa informasi yang sebenarnya tidak valid bahkan hoaks, begitu cepat menyebar. Ini karena sebagian masyarakat begitu mudah percaya, terlalu cepat membuat judgement, terburu-buru berkomentar dan bergegas membagikan ke kontak lain dalam jejaringnya. Lebih mengedepankan emosi, ketimbang logika.
Itulah repotnya. Akibatnya, kebiasaan berspekulasi terhadap sebuah peristiwa menebar cepat melalui media sosial, yang kerap menciptakan disinformasi di tengah masyarakat.
Apalagi, pengguna telepon genggam dengan mudah dapat membuat postingan tulisan, gambar atau video apa saja, lalu menyebarkannya. Bahkan banyak pula informasi dikemas dengan narasi palsu atau hoaks, tersebar dalam berbagai aplikasi pesan, terutama Whatsapp. Tak dipungkiri, disinformasi bagaikan wabah virus yang begitu cepat menyebar lewat genggaman kita.
Kondisi semacam itu telah berlangsung setidaknya sejak lima tahun terakhir, dan terasa begitu intensif saat Indonesia menggelar rangkaian pemilu serentak sejak sekitar satu tahun belakangan ini. Wabah informasi palsu, fake news dan hoax beredar cepat dan luas di tengah masyarakat.
Bahkan tatkala pemilihan umum anggota legislatif dan presiden – wakil presiden masa bakti tahun 2019 - 2024 telah berlalu, peredaran informasi palsu bukannya berhenti, malah bertambah intensif.
Kini, kita justru disuguhi banyak drama politik, hampir tiap hari. Ada yang menebar opini bahwa hitung cepat tak perlu dipercaya. Juga gerakan dan imbauan untuk tidak menonton televisi yang melansir hitung cepat alias Quick Count. Juga berbagai opini tentang penyelenggaraan pemilu yang dituduh curang secara membabi buta.
Berbagai opini tersebut tersebar secara sistematis, terstruktur, dan massive; melalui perangkat telepon genggam di tangan kita.
***
Saya kok percaya, opini publik terhadap banyak peristiwa –di bidang sosial, ekonomi, hukum dan politik— yang kemudian begitu mudah dipercaya (meskipun kerapkali sebenarnya keliru atau informasi palsu), sebagian terlahir akibat literasi digital yang rendah di sebagian besar masyarakat Indonesia.
Ada yang menyebut, Indonesia memang mengalami darurat literasi. Kemampuan membaca dan memahami konteks, bukan sekadar teks, relatif rendah. Kemampuan logika, yang tercermin dari skor pemahaman matematika, juga relatif rendah. Begitu pula dalam hal science.
Anda boleh saja tidak sependapat dengan premis itu. Tetapi, biar lebih valid, saya coba tunjukkan skor PISA Indonesia, yang ternyata jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga kita. Jangankan dengan Singapura yang menempati posisi terbaik dalam skor PISA, Indonesia jauh tertinggal dengan Thailand, bahkan dengan Vietnam.
PISA (The Programme for International Student Assessment) adalah survei internasional tiga tahun sekali yang digelar oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). PISA dimulai pertama kali tahun 2000, menilai seberapa baik siswa berusia 15 tahun di setiap negara dapat menerapkan pelajaran yang diperoleh di sekolah ke dalam situasi kehidupan nyata.
Para siswa itu diuji dalam tiga subyek penting, yakni reading, mathematics dan science. Asesmen PISA terakhir sudah dilakukan akhir tahun 2018 lalu, namun saat ini laporannya belum keluar, karena secara tradisi baru akan dipublikasikan pada Desember 2019 atau setahun setelah asesmen.
Namun, ada data sebelumnya, berdasarkan laporan terakhir asesmen tahun 2015. Dari data tahun 2015 itu, Singapura menduduki peringkat pertama Indeks PISA. Sekitar 1 dari 4 siswa di Singapura menempati kinerja terbaik dalam penguasaan science. Selain Singapura, negara seperti Kanada, Estonia, Finlandia, Hong Kong (China), Jepang, Macao (China), dan Vietnam, tercatat sedikitnya 9 dari 10 siswa menguasai pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap siswa sebelum meninggalkan sekolah. Indonesia tidak masuk kelompok ini.
Indonesia memang disebut masuk kelompok lima negara yang mengalami perbaikan sistem pendidikan tercepat di antara 72 negara dalam kurun waktu 2012 hingga 2015 itu. Anda bisa bayangkan, bagaimana kondisi Indonesia sebelumnya.
Indonesia juga dinilai mengalami kemajuan pesat dalam matematika. Namun demikian, dalam hal kemampuan membaca, perbaikan yang terjadi pada siswa Indonesia hanyalah moderat.
Secara keseluruhan, Indeks PISA Indonesia pada laporan 2015 itu berada pada peringkat 62 dari 72 negara dengan skor 403 untuk “Science”, 397 untuk “Reading” dan 386 untuk “Matemathics”. Jauh di bawah Vietnam yang memiliki skor masing-masing 525, 487 dan 495 untuk ketiga kategori tersebut.
***
Angka-angka skor PISA Indonesia itu tentu saja bukan cuma data kosong. Cara saya menafsirkannya, rendahnya skor “Matematika” dan “Membaca”, meski relatif baik dalam skor “Science” itu terimplikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari, dewasa ini.
Cara saya menafsirkan data itu, kemampuan menyerap bacaan dan logika sebagian besar masyarakat menjadi relatif lemah. Barangkali kondisi itulah yang dapat menjelaskan, literasi digital di Indonesia pun menjadi persoalan serius.
Kita bisa mengamati, begitu banyak orang yang terlalu mudah percaya terhadap sebaran informasi yang sesungguhnya tidak masuk akal. Bahkan ada riset yang menyebutkan, maaf, generasi tua di Indonesia lebih mudah mempercayai dan menebarkan hoaks ketimbang generasi milenial yang lebih kritis.
Oleh sebab itu, darurat literasi, terutama literasi digital, perlu upaya serius untuk mengatasinya.
Kebiasaan mencerna, bukan sekadar membaca, perlu terus menerus ditumbuhkan. Dan diingatkan. Kebiasaan berfikir kritis dan menggunakan logika, wajib dikedepankan. Kemampuan menahan diri untuk membagikan informasi yang belum bahkan tidak diyakini kebenarannya, haruslah terus ditularkan.
Namun, itu semua berpulang kepada sistem pendidikan yang lebih baik. Bukan sekadar menanamkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, tetapi juga menumbuhkembangkan nilai-nilai dan sikap positif dalam menyikapi berbagai keadaan.
Saya khawatir, apabila sistem pendidikan kita –formal maupun nonformal— gagal menanamkan nilai-nilai tersebut, bibit perpecahan dan sekat-sekat sosial-kultural akan kian menajam di tahun-tahun yang akan datang. Tentu, saya sangat penuh harap, perpecahan sosial itu tidak akan pernah terjadi di negeri tercinta ini.
Nah, bagaimana menurut Anda? (*)