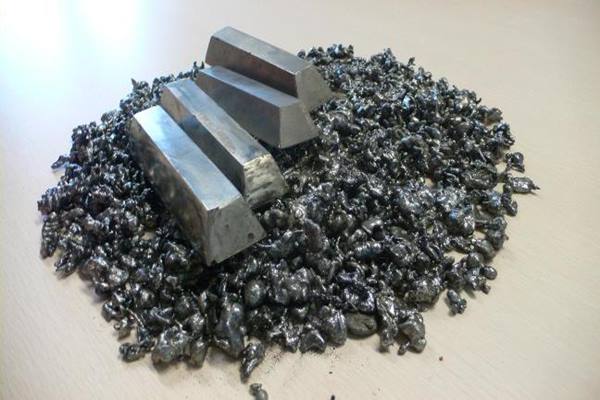Bisnis.com, JAKARTA - Sejak 1 Januari 2020, para penambang nikel dilarang melakukan ekspor bijih nikel berkadar rendah atau berkadar di bawah 1,7 persen.
Mau tak mau, para penambang nikel hanya berharap pada smelter lokal untuk dapat menyerap nikel berkadar rendah. Namun demikian, smelter lokal tak mau menyerap nikel berkadar rendah di bawah 1,8 persen.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan kondisi smelter yang tak mau menyerap nikel berkadar rendah atau dibawah 1,8 persen ini membuat para penambang banyak yang melakukan tambang ilegal. Penambangan ilegal ini dilakukan untuk mencari dan menambang nikel berkadar lebih dari 1,8 persen sehingga dapat diterima oleh smelter lokal.
"Ini fair-fairan saja kondisi saat banyak penambang nikel yang jadi tambang ilegal karena mencari kadar tinggi, dibabatnya hutan-hutan lindung yang akibatnya sekarang lingkungan rusak dan terjadi banjir di tambang Sulawesi Tenggara. Blok PT Vale Indonesia yang lagi ramai dilelang saat ini sudah habis ditambang. Ini enggak bisa dipungkiri karena penambang mau hidup, banyak kewajiban," ungkapnya dalam acara diskusi Prospek Industri Nikel Dalam Negeri, Jumat (28/2/2020).
Untuk dapat hidup, para penambang pun mau tak mau mencari dan menjual nikel berkadar 1,9 pesen. Nikel yang berkadar 1,9 persen yang dikirim ke smelter, lanjutnya, tetap saja ditolak oleh smelter karena hasil pemeriksaan surveyor yang ditunjuk disebut kadarnya di bawah 1,8 persen.
"Kalau hasil surveyor mereka menyebut kadar kita dibawah 1,6 persen kami kena denda US$12 per metrik ton. Yang tadinya kami menerima bayar US$2,4 miliar untuk 1 tongkang, ternyata kami harus bayar US$1,4 miliar ke smelter untuk 1 tongkang," ucapnya.
APNI, lanjutnya, tak pernah menolak ekspor dilarang atau tidak. Namun, selama ini tak keadilan untuk para penambang nikel. Smelter yang berdiri di Indonesia diharapkan dapat membuat para penambang nikel dapat hidup tetapi yang ada malah para penambang menjadi rugi.
Dia menuturkan apabila dilakukan perbandingan harga ekspor, lokal dan pajak di mana harga ekspor nikel berkadar 1,8 persen untuk free on board (FoB) sebesar US$60 per metrik ton. Lalu para penambang dikenakan kewajiban HPM untuk nikel 1,8 persen sebesar US$30 per metrik ton yang harus dilakukan sebelum kapal berlayar.
Smelter, lanjutnya, menerima nikel berkadar 1,8 persen FoB sebesar US$18 per metrik ton.
"Saat ini kontrak menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF). Pada Januari lalu kontrak CIF untuk nikel berkadar 1,8 persen di dua smelter raksasa sebesar US$26 per metrik ton. US$26 per metrik ton ini untuk bayar biaya tongkang, biaya surveyor, biaya muat, bongkar, habis juga," katanya.
Para smelter memberikan iming-imimg bonus untuk nikel yang kadarnya tinggi dan juga diberikan penalti atau denda apabila kadar nikel di bawah 1,8%. Seringkali nikel yang dikirim oleh penambang selalu direject karena berada di bawah ketentuan 1,8 persen.
"Smelter tak pernah menggunakan surveyor yang ditentukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Kami bayar royalti, bayar kewajiban dan lain-lain menggunakan surveyor yang ditentukan pemerintah. Smelter pakai surveyor lain, ujung-ujung kadar kami di-reject," ujarnya.
Selama ini, 99 persen kargo nikel yang dikirim ke smelter selalu ditolak karena surveyor smelter selalu menyebut kadar nikel di bawah 1,8 persen. Bijih nikel yang ditolak oleh smelter tersebut kerap kali tak dibawa balik oleh para penambang karena besarnya biaya untuk memuat kembali dan biaya tongkang.
"Kalau ditanya sudah bakar dan enggak ada. Hilang. Sudah digunakan smelter. Artinya, smelter lokal bisa menyerap kadar 1,8 persen di bawah. Kami minta pemerintah hadir di sini. Ini enggak bisa dibilang B to B. Kalau B to B, jangan bebankan kami bayar pajak royalti berdasarkan HPM (harga patokan mineral) tetapi harga kontrak," tutur Meidy.