Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah bank besar berskala global bermarkas di Jerman menjadi bank pertama yang memberikan sinyal awal tentang perkiraan resesi Amerika Serikat (AS), meskipun bobotnya tergolong ringan. Potensi resesi ekonomi AS sebagai konsekuensi upaya The Federal Reserve Bank (The Fed) menekan inflasi yang melambung tinggi mencapai 8,5 persen.
Masalahnya, masih menurut bank tersebut, dibutuhkan waktu lama untuk memaksa inflasi turun menuju sasaran sebesar 2 persen. Langkah menaikkan suku bunga acuan, Fed Fund Rate (FFR), sudah ditempuh untuk mengerem inflasi. Tidak tanggung-tanggung, dalam dua kali pertemuan pengambil kebijakan, The Fed menaikkan FFR sebesar 75 basis poin.
Diyakini The Fed tetap akan agresif menaikkan FFR setidaknya dalam empat-lima kali pertemuan di tahun ini hingga FFR menyentuh kisaran 2,0 persen—2,5 persen.
Ini pilihan sulit dan dilematis yang harus ditempuh, karena tidak ada solusi lain yang lebih efektif untuk mengerem inflasi. Langkah The Fed itu menandai berakhirnya rezim kebijakan moneter longgar (dovish) dan mulai diterapkan kebijakan moneter yang condong ketat (hawkish).
Pengetatan kebijakan moneter di mana pun akan menahan kegiatan perekonomian dalam arti luas karena dua alasan. Pertama, pemilik dana akan menghentikan atau setidaknya mengurangi porsi anggaran untuk investasi sehingga volume perekonomian melandai. Kedua, para pelaku usaha cenderung menahan ekspansi bisnis untuk mengurangi beban kewajiban terhadap perbankan. Maklum, sudah lazim kenaikan suku bunga bank sentral akan diikuti kenaikan suku bunga perbankan, khususnya suku bunga kredit.
Jika langkah The Fed terlalu agresif sehingga kenaikan FFR menjadi terlalu tinggi (overshoot), maka akan melambatkan ekonomi AS secara ekstrem sehingga bisa berpotensi menuju resesi, yakni pertumbuhan ekonomi kuartalan terkontraksi (negatif) selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini bukan ilusi karena perekonomian AS pernah mengalami resesi ketika terjadi global financial crisis dan bahkan great depression.
Baca Juga
Ironisnya, rujukan kebijakan moneter di negara-negara lain pada umumnya mengacu kepada arah gerak kebijakan The Fed. Hal ini sudah terjadi berkali-kali baik saat perekonomian global berada pada fase kontraksi maupun fase ekspansi. Jika demikian, hampir pasti aktivitas perekonomian akan melemah di saat laju inflasi belum sepenuhnya dapat dikendalikan ke level yang ditargetkan. Itulah yang disebut dengan stagflasi. Ujung-ujungnya, angka pengangguran akan kembali naik, yang justru terjadi ketika pandemi Covid-19 hampir berakhir sepenuhnya.
Saat ini inflasi di sejumlah negara maju menunjukkan level yang tidak biasa, jauh lebih tinggi dari ekspektasi atau konsensus. Pengambil kebijakan di negara-negara maju, termasuk bank sentralnya, terkejut ketika laju inflasi meroket di luar pakemnya. Adalah perang Rusia dan Ukraina yang menjadi pemantik lonjakan inflasi di berbagai negara. Perang telah menciptakan gangguan hebat pada rantai pasok global sehingga mendorong kenaikan harga barang dan komoditas secara langsung.
Gangguan distribusi global ini memicu lonjakan ongkos transportasi sehingga menciptakan cost push inflation dan imported inflation secara bersamaan. Bahkan AS dan Jerman sebagai dua negara adidaya ekonomi dengan sistem logistik nasional yang efisien pun didera kenaikan inflasi yang luar biasa masing-masing menyentuh level 8 persen. Harga minyak mentah dunia yang menembus level US$100 per barel pun disebabkan gangguan distribusi di pasar minyak dunia.
Ancaman stagflasi berpotensi merembet ke pasar saham karena arah investasi portofolio sebagian investor beralih ke instrumen non-saham. Beberapa lembaga internasional yang bergerak di sektor keuangan pun sudah memberikan sinyal awal tentang resesi yang sepertinya tidak bisa dihindari.
Sebagian analis dan ekonom memang menilai bahwa perkiraan tentang krisis ekonomi AS dan stagflasi global terlalu dilebih-lebihkan. Tetapi, melihat data ekonomi terkini mengacu pada laju inflasi yang ekstrem, kebijakan responsif rasanya perlu dilakukan.
Seorang ekonom dari Goldman Sachs dalam sebuah laporannya mengatakan bahwa upaya menurunkan inflasi sangatlah menantang, meskipun resesi ekonomi sebagai buah “kebijakan anti pertumbuhan” sulit dihindari. Persisnya, siapa pun tidak membutuhkan resesi, tetapi mungkin memang membutuhkan pertumbuhan untuk melambat ke kecepatan yang di bawah potensinya.
Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management juga berharap ekspansi ekonomi terus berlanjut meskipun The Fed beralih ke stance kebijakan yang hawkish untuk memerangi lonjakan inflasi. Maklum, jika inflasi tetap tinggi, maka The Fed akan dipaksa untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan yang lebih dramatis.
Para ekonom menengarai, sumber lonjakan inflasi kian beragam, yaitu deglobalisasi, perubahan iklim, gangguan rantai pasokan global sebagai dampak perang di Ukraina serta kebijakan penguncian (lockdown) atas pandemi Covid-19 di China. Semua itu membangun ekspektasi inflasi yang tinggi sehingga perlu pengendalian segera secara komprehensif.
Bank-bank sentral pun merespons dengan menaikkan suku bunga acuan. Selaras dengan langkah The Fed, maka bank sentral Inggris, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia pun sudah menaikkan suku bunga acuannya.
Peringatan Bernanke
Dalam pandangannya yang dimuat di harian New York Times edisi 16 Mei 2022, Ben Bernanke, mantan ketua The Fed selama krisis keuangan 2008, memperingatkan bahwa AS dapat menuju periode stagflasi. Menurutnya, ekonomi AS untuk pertama kalinya sejak 1970-an bisa menuju periode stagflasi.
Pada saat itu orang Amerika kehilangan pekerjaan, tetapi masih menghadapi harga yang lebih tinggi di toko kelontong dan di pompa bensin. Bahkan di bawah skenario sederhana, pengambil kebijakan harus memperlambat roda perekonomian untuk menghambat laju inflasi.
Bernanke menyimpulkan, harus ada periode dalam 1—2 tahun ke depan di mana pertumbuhan ekonomi AS rendah, pengangguran naik sedikit, dan inflasi masih tinggi. Pandangan ini senada dengan Larry Summers dan Jason Furman, mantan penasihat ekonomi pemerintahan Barack Obama, bahwa resesi kemungkinan terjadi.
Namun, Bernanke masih berharap resesi bisa dihindari. Diyakini bahwa ancaman lebih besar terhadap ekonomi AS adalah stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi inflasi tetap tinggi. Maka, jangan sekali-kali mengabaikan risiko yang meningkat. Peringatan ini menjadi penegas bagi pengambil kebijakan di AS dan di negara-negara maju lainnya, yang pernah didera resesi pada 2008 (global financial crisis).
Setidaknya ada dua indikator ekonomi yang bisa dijadikan sebagai sinyal risiko yang meningkat yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan, investor dan konsumen. Pertama, tingkat tabungan pribadi—atau persentase pendapatan sekali pakai konsumen yang ditabung setiap bulan—telah turun menjadi 4,4 persen pada April lalu, yang merupakan level terendah sejak September 2008, ketika Lehman Brothers bangkrut. Sebagai perbandingan, menurut penelitian dari Federal Reserve St. Louis, dari 1959 hingga 2019 tingkat tabungan pribadi rata-rata 11,8 persen.
Kedua, inflasi tetap mendekati level tertinggi dalam empat dekade, dan The Fed akan terus menaikkan suku bunga acuan sampai, seperti yang dikatakan Ketua The Fed Jerome Powell, ada bukti “jelas dan meyakinkan” bahwa inflasi terkendali pada target sasaran sebesar 2 persen.
Untuk itulah kredibilitas The Fed dalam menetapkan kebijakan sangat penting untuk melawan inflasi. Paralel dengan langkah tersebut, diharapkan pula masalah rantai pasokan global dapat diselesaikan. Hal ini membutuhkan kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina dengan sokongan para negara pendukung masing-masing.
Diplomasi politik menuju langkah damai menjadi kunci utama menstabilkan perekonomian global sehingga ancaman resesi atau stagflasi dapat dihindarkan. Pemerintah AS menjadi aktor penting untuk mengambil peran terciptanya langkah damai tersebut. Paralel dengan itu, pemerintahan Joe Biden juga dituntut untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan terkait pengenaan tarif untuk barang impor dari China.
Jadi, akankah terjadi resesi global? Belum, kata para ekonom global. Resesi global tidak akan segera terjadi, tetapi bersiaplah untuk menghadapi kenaikan biaya dan pertumbuhan yang lebih lambat. Simon Baptist, kepala ekonom global di Economist Intelligence Unit (EIU), merujuk pada resesi yang mengejutkan setelah periode stagflasi.
Ketika berlangsung perang di Ukraina dan pandemi Covid-19 terus mengganggu pada rantai pasokan global, maka stagflasi—ditandai dengan pertumbuhan rendah dan inflasi yang tinggi—akan bertahan “setidaknya selama 12 bulan ke depan.” Harga komoditas akan mulai mereda mulai kuartal depan, tetapi akan tetap lebih tinggi secara permanen daripada sebelum perang di Ukraina karena alasan sederhana bahwa pasokan dari Rusia terkait komoditas akan berkurang secara permanen.
Pandemi dan perang di Ukraina telah menghambat pasokan komoditas dan barang sehingga mendisrupsi distribusi yang efisien melalui rantai pasokan global, yang pada gilirannya memaksa kenaikan harga barang sehari-hari seperti kelompok bahan bakar dan makanan.
Namun, sementara harga yang lebih tinggi akan menyebabkan rasa sakit bagi sebagian rumah tangga, tetapi pertumbuhan di banyak bagian dunia, meskipun melambat, masih terus berdetak, dan pasar kerja belum runtuh. Ini lantaran tingkat pengangguran di banyak negara telah mencapai level terendah dalam beberapa dekade.



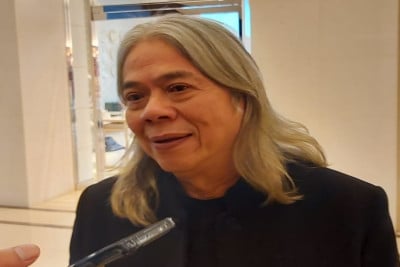




















-19-ant-01tol.jpg?w=300&h=221)
